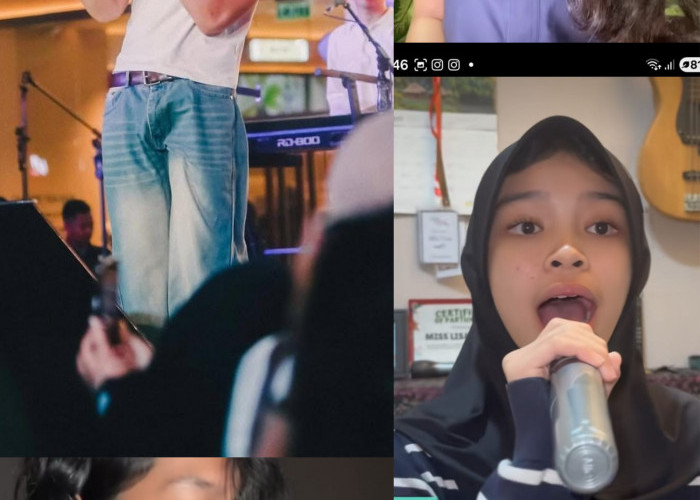Epitaph: Syair untuk Sebuah Zaman dan Peringatan dari Alam

Ahmad Sihabuddin-Istimewa-
Ekologi Kritis: Alam sebagai Korban Modernitas
Di sinilah Epitaph menjadi lagu protes yang sunyi, tanpa slogan, tanpa agitasi, tetapi justru lebih mengganggu, karena ia memaksa kita bercermin.
Jika krisis generasi 1960-an diwujudkan dalam Perang Vietnam, krisis kita hari ini menjelma dalam bencana ekologis. Banjir bandang di Sumatra, longsor, tragedi kawasan wisata Guci di Tegal, dan kemarin di Kecamatan Cisarua KabupatenBandung Barat terjadi tanah longsor menutup dua dusun, ini bukan sekadar musibah alam. Dalam perspektif ekologi kritis, bencana-bencana itu adalah produk relasi timpang antara manusia dan alam.
Alam tidak lagi diperlakukan sebagai mitra hidup, melainkan sebagai komoditas. Hutan menjadi angka dalam laporan investasi, sungai menjadi saluran limbah, gunung menjadi objek wisata tanpa etika daya dukung. Semua dilakukan atas nama “ilmu”, “perencanaan”, dan “pembangunan”, sekali lagi membenarkan peringatan Epitaph tentang ilmu yang berbisa.
Kearifan Lokal Sunda–Jawa: Harmoni yang Terlupakan
Menariknya, apa yang dikritik Heidegger dan Adorno sebenarnya telah lama diperingatkan dalam kearifan lokal Nusantara, khususnya Sunda dan Jawa.
Dalam tradisi Sunda dikenal prinsip “silih asih, silih asah, silih asuh”, relasi timbal balik antara manusia, sesama, dan alam. Alam bukan objek mati, melainkan bagian dari tatanan kosmis yang harus dijaga. Konsep leuweung larangan (hutan larangan) adalah bentuk etika ekologis tradisional: ada wilayah yang tak boleh disentuh demi keseimbangan hidup.
Dalam kosmologi Jawa, manusia hidup di antara jagad alit (mikrokosmos) dan jagad gede (makrokosmos). Ketika keseimbangan ini rusak, yang muncul bukan hanya bencana alam, tetapi juga kekacauan sosial dan batin. Prinsip eling lan waspada, ingat dan waspada, adalah peringatan agar manusia tidak terbuai oleh kesombongan kuasa.
Jika kearifan ini dibaca ulang, Epitaph seolah bukan lagu Barat semata, melainkan ratapan universal yang juga relevan dengan tanah Sunda dan Jawa.
Dari Nisan Menuju Kesadaran
“Epitaph” tidak menawarkan solusi teknis. Ia tidak memberi resep kebijakan atau cetak biru pembangunan. Hanya menawarkan, kesadaran akan batas, bahwa manusia bukan penguasa mutlak, melainkan bagian dari jejaring kehidupan.
Dalam bahasa Heidegger, kita perlu kembali menghuni dunia, bukan sekadar menguasainya. Dalam bahasa Adorno, kita perlu mencurigai rasio yang terlalu percaya diri. Dalam bahasa kearifan lokal Sunda–Jawa, kita perlu eling, menjaga harmoni, dan tahu kapan harus berhenti.
Jika tidak, lagu ini akan terus relevan, bukan sebagai nostalgia, melainkan sebagai syair untuk nisan peradaban kita sendiri.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: