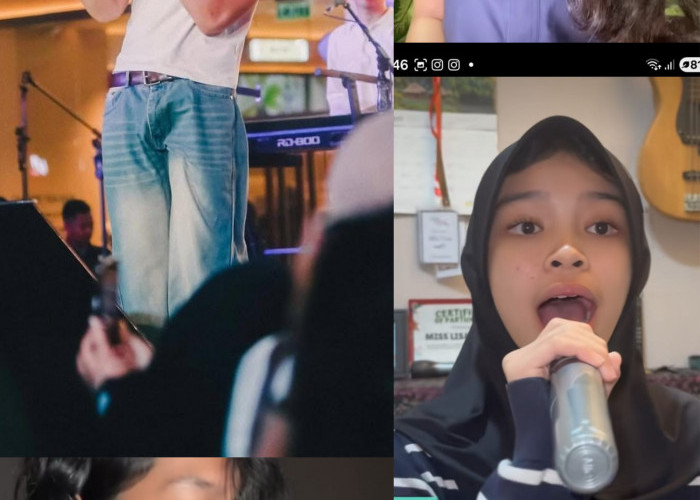Epitaph: Syair untuk Sebuah Zaman dan Peringatan dari Alam

Ahmad Sihabuddin-Istimewa-
Oleh: Ahmad Sihabudin, Dosen Komunikasi Lintas Budaya, FISIP, Untirta
Ada lagu yang tak pernah benar-benar selesai didengarkan. “Epitaph” karya King Crimson adalah salah satunya. Ia bukan sekadar artefak musik progresif rock dari akhir 1960-an, melainkan kidung murung tentang manusia modern yang kehilangan pijakan. Nada murung yang mengalun pelan, hampir seperti kidung pemakaman, membawa pendengarnya pada ruang batin yang sunyi dan penuh tanya.
Jika dibaca secara utuh, liriknya menyerupai syair untuk sebuah nisan, nisan peradaban yang terlalu percaya pada kemajuan, tetapi lupa pada kebijaksanaan. Lagu King Crimson, ini menempati track ketiga album legendaris In the Court of the Crimson King (1969).
Greg Lake, komposer lagu ini, menyebut Epitaph sebagai ungkapan kebingungan melihat dunia yang kian gila. Kebingungan itu lahir dari pengalaman generasi pasca-Perang Dunia II: sebuah generasi yang dijanjikan kedamaian, tetapi justru mewarisi konflik baru, terutama Perang Vietnam.
Di tengah krisis iman, baik iman religius maupun iman pada rasio, banyak anak muda Barat kala itu melarikan diri ke LSD dan mariyuana, mencari surga semu, kedamaian instan, dan realitas alternatif.
Namun pelarian itu, sebagaimana ditegaskan Epitaph, hanyalah gejala dari keterasingan manusia modern dari makna hidupnya sendiri.
Ketika Dunia Menjadi Sekadar Objek
Dalam filsafat Martin Heidegger, krisis modernitas bukan semata soal teknologi, melainkan soal cara manusia memahami keberadaan. Heidegger menyebut modernitas sebagai zaman Gestell, kerangka berpikir yang menjadikan segala sesuatu, termasuk alam dan manusia, sebagai “standing reserve”, cadangan yang siap dieksploitasi.
Nada murung Epitaph sejalan dengan kegelisahan Heidegger. Dunia yang digambarkan Lake adalah dunia yang tak lagi “dihuni” (dwelling), melainkan dikelola, dihitung, dan dikendalikan. Dalam kondisi ini, manusia kehilangan hubungan puitiknya dengan semesta. Ia tahu banyak hal, tetapi tidak lagi mengerti.
Maka lirik yang saya ingat dalam lagu tersebut terasa sangat Heideggerian; “Knowledge is a deadly friend, if no one sets the rules.” Ilmu pengetahuan, tanpa kebijaksanaan ontologis dan etis, justru mempercepat keterasingan manusia dari dirinya sendiri dan dari alam.
Rasio yang Berbalik Menjadi Petaka
Bila Heidegger mengkritik teknologi dari sisi ontologis, Theodor W. Adorno, bersama Max Horkheimer, melihatnya dari sisi sosial dan politik. Dalam Dialectic of Enlightenment, Adorno menyatakan bahwa rasio yang dibebaskan dari mitos justru menciptakan mitos baru: mitos kemajuan, efisiensi, dan dominasi.
Nada muram Epitaph adalah gema dari kritik Adorno: pencerahan yang seharusnya membebaskan manusia malah melahirkan kekerasan baru. Ilmu pengetahuan tidak netral; ia bisa menjadi alat pembebasan, tetapi juga alat penghancuran. Dari bom atom hingga perusakan ekologis, rasio instrumental menunjukkan wajah gelapnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: