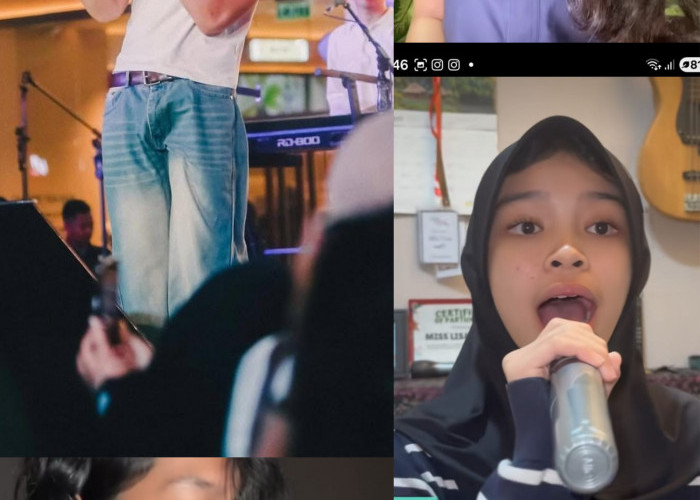Ketika Dunia Berhenti Bertepuk Tangan, Bagaimana Rasanya Sekarang?

Ahmad Sihabuddin-Istimewa-
Oleh Ahmad Sihabudin, Dosen Ilmu Komunikasi Untirta
Dulu kau berdiri di balkon tinggi kehidupan. Di bawahmu, manusia-manusia lain tampak kecil, bukan karena mereka rendah, melainkan karena kau ditempatkan terlalu tinggi.
Dari sana, kau biasa menunjuk arah, memberi nasihat, dan menamai apa yang kau sebut sebagai “realitas”. Dunia terasa lurus, tertata, dan sopan. Semua berjalan sesuai rencana, selama rencana itu milikmu.
Bob Dylan membuka Like a Rolling Stone dengan nada ejekan yang tidak kejam, tetapi telanjang. Ia tidak memaki; ia hanya bertanya: bagaimana rasanya ketika semua itu lenyap? Ketika dunia berhenti memanjakanmu. Ketika nama besarmu tak lagi membuka pintu. Ketika hidup menolak mengenalmu.
Pertanyaan itu, dalam masyarakat kita, sering dianggap tidak sopan. Sebab kita dibesarkan untuk percaya bahwa “yang pernah berjaya” pantas terus dihormati, betapapun kosong jejaknya. Kita terlalu sering menghormati masa lalu, bahkan ketika masa lalu itu gagal mempertanggungjawabkan dirinya di masa kini.
Namun hidup, seperti lagu Dylan, tidak sentimental. Ia menggelinding. Di titik inilah lirik satire lagu ini bekerja: bukan untuk menghina kejatuhan, melainkan menyingkap kepalsuan rasa aman. Mereka yang dulu merasa “di dalam”, kini tiba-tiba berada “di luar”. Mereka yang biasa bicara tentang meritokrasi, mendadak menyadari bahwa dunia tidak selalu adil, padahal ketidakadilan itu dulu menguntungkan mereka.
Dan di tengah kejatuhan itu, suara Kahlil Gibran terasa relevan, lirih namun menusuk. “Semakin dalam duka mengukirmu, semakin banyak kebahagiaan yang dapat kautampung.”
Gibran tidak sedang meromantisasi penderitaan. Ia sedang mengingatkan bahwa manusia baru sungguh-sungguh menjadi manusia ketika lapisan-lapisan palsu dilucuti. Ketika gelar, kuasa, dan simbol-simbol sosial runtuh, barulah seseorang berhadapan dengan dirinya sendiri, tanpa dekorasi.
Masalahnya, tidak semua orang siap. Maka ketika kejatuhan datang, banyak yang meratap bukan karena kehilangan makna, melainkan karena kehilangan status. Bukan karena hilang peran, tetapi karena hilang pengakuan. Dunia yang dulu dipanggil “tidak tahu diri” kini terasa kejam, hanya karena ia berhenti memuja.
Di sinilah Like a Rolling Stone berubah menjadi cermin sosial. Sebab bukankah kita hidup di masyarakat yang terlalu mencintai orang sukses, tetapi malas mendengarkan orang jatuh?
Kita memuja pencapaian, namun tidak sabar pada proses. Kita mengutip motivasi, tetapi alergi pada kerentanan. Maka ketika seseorang menggelinding jatuh dari singgasananya, yang tersisa sering kali hanyalah bisik-bisik sinis dan penghakiman murahan.
Padahal, menurut Gibran, kejatuhan bukan akhir, melainkan peralihan kesadaran. “Jika kamu ingin mengetahui Tuhan, janganlah mencari-Nya dalam awan-awan, tetapi temukanlah Dia dalam hatimu yang hancur.”
Hati yang hancur, bukan karena kalah bersaing, melainkan karena kehilangan ilusi, itulah ruang pembelajaran. Namun manusia ”sukses”, yang terlalu lama hidup dari citra, sering tidak tahan berada di ruang sunyi itu. Ia ingin segera kembali naik, kembali dikenal, kembali dipuja.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: